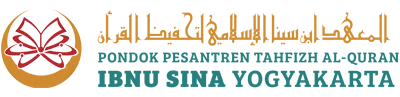Ketika Al-Qur’an Membelenggu, Bukan Merahmati
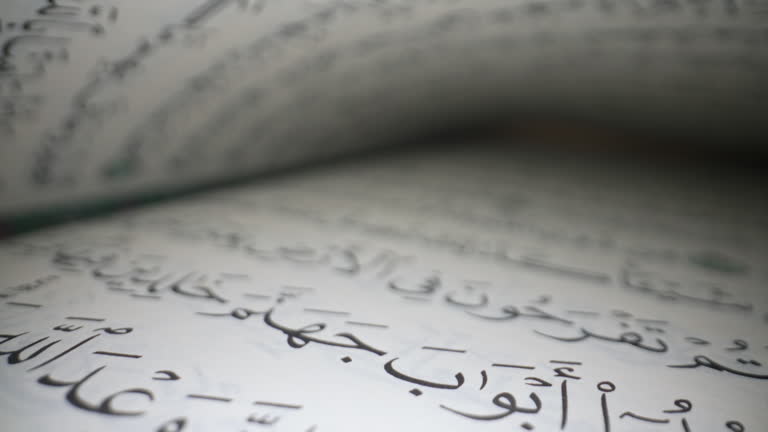
Oleh: KH. Roehan Usman (Pimpinan PP Ibnul Qoyyim Yogyakarta)
Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman as-Sulami, disebutkan bahwa para sahabat seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas‘ud dan yang lainnya tidak akan melanjutkan hafalan sepuluh ayat Al-Qur’an dari Nabi sebelum mereka memahami dan mengamalkan kandungannya. Mereka belajar Al-Qur’an tidak hanya sebagai bacaan, tapi sebagai ilmu dan amal sekaligus.
Semangat para sahabat dalam menerima dan menghafal Al-Qur’an begitu besar. Mereka merasa bangga jika telah menguasai surat-surat panjang seperti Al-Baqarah dan Ali ‘Imran. Bagi mereka, hafalan bukanlah sekadar tumpukan ayat, tetapi kehormatan dan tanggung jawab. Pemahaman dan pengamalan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari proses tersebut.
Cuplikan kisah di atas diambil dari pengantar kitab Mabahits fi Ulumil Qur’an karya Syaikh Manna’ Khalil al-Qaththan. Sebuah kitab pokok yang kini menjadi pegangan dalam pelajaran Ulumul Qur’an di kelas 4 dan 5 di PP Ibnul Qoyyim, Yogyakarta. Sementara di kelas 6, pelajaran Al-Qur’an diakhiri dengan pengkajian Tafsir, menggunakan pendekatan Tafsir Madrasi. Kedua pelajaran ini baru diterapkan dalam dua tahun terakhir sebagai respons atas keprihatinan terhadap pelajaran “tahfidz” yang selama ini berkembang di pondok.
Sejatinya, setiap mata pelajaran memiliki dua tujuan: Ghordul ‘Aam (tujuan umum) dan Ghordul Khash (tujuan khusus). Dalam konteks rumpun pelajaran Al-Qur’an, tahfidz semestinya menjadi pelengkap bagi tujuan umum, yakni menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dari Allah untuk membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya, ke jalan yang lurus. Sementara tujuan khususnya adalah agar santri memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an secara benar. Ini seperti dijelaskan oleh Dr. Muhammad Abdullah Daraz: bahwa Al-Qur’an disebut Qur’an karena dibaca dengan lisan, dan disebut Al-Kitab karena ditulis dengan pena. Keduanya menjadi instrumen penjaga satu sama lain, agar tidak terjadi penyimpangan, baik dalam hafalan maupun tulisan.
Namun, ketidaktepatan dalam merumuskan tujuan umum dan khusus pelajaran tahfidz inilah yang menjadi akar dari keprihatinan. Pelajaran tahfidz di pondok cenderung berdiri sendiri, terlepas dari ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, balaghah, serta ilmu pelengkap lainnya seperti Ulumul Qur’an, tafsir, hingga Ulumul Hadis. Hafalan menjadi fokus utama, bahkan satu-satunya, sehingga kualitas menjadi terabaikan. Akibatnya, tak jarang santri bisa menghafal puluhan juz, tapi tidak mampu menuliskannya dengan benar, apalagi menjelaskan maknanya.
Meski realitas seperti itu ada, namun semangat menghafal di kalangan santri tetap tinggi, begitu pula antusiasme para ustadz dalam membimbing mereka. Progres yang lambat dan kualitas yang kurang pun tidak menyurutkan langkah. Namun, ketika hafalan menurun secara kuantitas, tekanan psikologis mulai dirasakan. Santri merasa tertekan karena hafalannya berjalan lambat, sementara ustadz merasa usahanya belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Ironisnya, untuk mengatasi stagnasi tersebut, solusi yang diambil justru seringkali keliru: menambah jam pelajaran tahfidz, memperketat jadwal, mengundang motivator hafidz dari luar, hingga menambah anggaran. Semua itu dilakukan dalam rangka membentuk budaya tahfidz, tetapi tanpa koreksi atas arah dan tujuan pembelajarannya.
Problematika semacam ini adalah gambaran kecil dari keresahan penulis atas kondisi tahfidz yang berkembang. bisa jadi, dirasakan oleh sebagian guru di sekolah atau madrasah lainnya. Ketika penulis berdiskusi dengan Ust. Khairul Imam, Pengasuh PP Tahfidz Ibnu Sina, Moyudan, beliau menyampaikan satu pesan penting: “Program tahfidz harus didukung oleh tiga komponen, yaitu musyrif, santri, dan orang tua.”
Musyrif harus ikhlas membimbing, bersih dari riya dan sum’ah. Santri harus memiliki kesadaran pribadi, bukan karena keterpaksaan. Dan orang tua perlu mendukung secara lahiriah (materi) dan batiniah (doa dan spiritualitas), karena menghafal Al-Qur’an adalah pekerjaan besar yang memerlukan tenaga, waktu, dan ketekunan spiritual yang tinggi.
Banyak teori menyebut bahwa tahfidz dapat menumbuhkan kecerdasan spiritual. Dengan seringnya berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur’an, seseorang akan terbentuk kesadarannya, yang kemudian menjadi dasar bagi tumbuhnya kecerdasan emosional dan intelektual. Namun untuk membuktikan hal ini dalam konteks pondok pesantren, tentu dibutuhkan riset yang serius dan mendalam.
Sebaliknya, ada pula teori yang menyebut bahwa hafalan bisa menumpulkan nalar, jika tidak diimbangi dengan pemahaman. Hafalan semata bisa menjadikan siswa hanya menjadi ‘penyimpan data’, bukan pemikir yang reflektif. Maka, penting untuk menggabungkan hafalan dengan pemahaman, serta melatih santri mengaplikasikan isi Al-Qur’an dalam konteks kehidupan nyata.
KH. Hisyam Syafi’i, pendiri PP Ibnul Qoyyim Yogyakarta, dulu sering menasihati para santrinya, “Le, lek kowe wes paham Al-Fatihah lan Al-Baqarah, insyaAllah kowe gampang memahami Al-Qur’an.” Sebuah nasihat sederhana namun sarat makna: sedikit ilmu yang dipahami dengan baik, jauh lebih berarti daripada banyak hafalan yang tidak membekas dalam jiwa.
Kini, dengan menjamurnya program tahfidz sebagai ‘unggulan’ di banyak lembaga pendidikan, tak sedikit yang akhirnya menjadikannya sekadar alat branding. Alih-alih menjadi rahmat, program tahfidz malah menjadi beban bagi santri, ustadz, dan bahkan lembaga. Hanya segelintir lembaga yang benar-benar menjadikan tahfidz sebagai bagian dari misi besar: menjadi agen penjaga Al-Qur’an sekaligus inspirator rahmat bagi semesta.